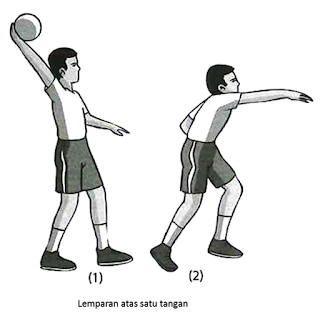Puisi Reruntuhan Kedaton, Yang Dibungkus, Gunung Wurung, Demi Obituari
Gresik: Telur Bebek dan Leher
Ada amsal tentang kenangan awal. Kenangan pada jajaran rumah yang berubin tebal dan bertembok tinggi. Serta patung kilin yang bersiaga di tempat ibadah. Patung kilin yang menyimpan wujud mustika di delapan- belas bagian tubuhnya. Juga tentang telur-telur bebek yang tergeletak di sepanjang got kering sebelah trotoar.Telur-telur bebek yang dipunguti oleh tangan si kanak. Tangan yang kini telah dewasa. Yang diam-diam juga ingin memetik matahari sebelum lingsir. Atau mewarnai kulit delima agar tetap merona. Semerona ibu yang telah menjadi bidadari. Bidadari yang setiap bersedih, berziarah ke makam Tuan Maulana. Dengan air mata berlinang. Juga dengan kerudung yang berjuntai menawan.

Dan ada amsal tentang kenangan berikutnya. Kenangan pada aroma yang memberat. Seberat napas yang membau sengak. Yang mengingatkan bau asap yang mengepul dari sekian cerobong. Sekian cerobong, yang jika gerhana tiba, bergerak dan berjalan tegap. Seperti seregu serdadu yang baris-berbaris. Berderap. Berderap. Berderap. Dan sesekali memeragakan kerancakan jalan di tempat. Kerancakan yang membuat permukaan pantai jadi bergoyang. Sampai tiga ikan buntal yang berenang, pun seketika membuntalkan perutnya. Sebab menganggap, ada musuh yang akan menyergap. Musuh yang mungkin terang. Mungkin gelap. Atau malah mungkin samar. Tapi amat dekat. Sedekat urat di leher.
(Gresik, 2016)
(Gresik, 2016)
Reruntuhan Kedaton
Setelah menyesap kopi. Setelah membaca pesan pendek
yang masuk: ”Di mana Kamu?” Setelah mengetahui, jika
pohon-pohon delima di bukit sudah jarang tumbuh. Dan
setelah merasa, jika kursi yang terduduki mulai hangat.
Maka, terlihatlah daun-daun pring kering yang melayang
ringan. Jatuh ke reruntuhan kedaton. Menangkup di tanah.
Lalu setelah kembali menyesap kopi. Setelah melambai pada
yang tiba-tiba lewat. Setelah melihat jam yang menunjuk
pukul satu siang. Dan setelah menggeliat sebentar. Maka,
teringatlah pada sepasang naga (yang kabarnya) melata
pelan ke gerbang reruntuhan kedaton. Terus menggaib
di tempat. Menggaib dengan mulut menganga. Seakan
ingin mencaplok yang datang dengan niat buruk.
Apalagi ingin berlagak tanya: ”Kenapa undak-undakan
ke reruntuhan kedaton tak bisa dihitung dengan pasti?”
Setelah tak ada lagi yang ditunggu. Setelah segalanya mesti
beranjak. Dan setelah membaca pesan pendek yang kembali
masuk: ”Di mana Kamu? Balas.” Maka, setiap yang menegak
di sekitar reruntuhan kedaton merunduk. Merunduk pada
seratus kuda yang tiba-tiba melintas di langit. Seratus kuda
yang gagah. Yang dulu turut berjaga di jalan-jalan pintas
ke bukit. Sebelum penyerangan itu terjadi. Sebelum pada
akhirnya semua gugur. Dan dimakamkan dengan nisan-nisan
yang bertulis huruf samar. Huruf yang mirip lebah. Lebah
lembut yang diam-diam menyelinap ke kuping yang ada. Terus
ke jantung. Membikin sarang madu di kedalamannya. Dan
sesekali, akan keluar mencari nektar untuk diserap. ”Hmm,
sarang madu di kedalaman jantung, adakah yang mafhum?”
(Gresik, 2016)
Yang Dibungkus
Ketika meraba kue itu, aku teringat hatimu. Hati yang
pulen. Yang legit. Dan yang dibungkus daun ope
kering persegi. Seperti bungkusan jimat yang dipaku
di atas jendela. Jimat penangkal jin demam dan pilek.
Jin demam dan pilek yang berwujud seperti kartu-kartu
domino. Dengan bulatan lima-enam, satu-tiga, empat-dua,
atau malah balak kosong. Kartu-kartu domino yang
dimainkan di gardu. Dengan gandulan di daun telinga bagi
yang kalah. Dan ketika mengudari bungkus kue itu, aku
juga teringat hatimu. Hati yang berwarna putih tulang.
Putih ngedop. Putih yang sedikit menggoda. Juga sedikit
membuat si pacar cemburu. Pada kabar yang tak jelas.
Tentang si orang lain yang lebih terlihat menawan.
Dan yang lebih terlihat pintar berpuisi dan bercakap.
Padahal, mana ada janji yang menikung, jika jalan
terpilih sudah dibentang. Jalan lurus yang menuju ke arah
yang diangan. Lalu ketika menyuguhkan kue itu,
aku (sekali lagi) juga teringat hatimu. Hati yang sesekali
kau suapkan ke mulutku. Sambil tersenyum renyah. Dan
berbisik: ”Makanlah hatiku, biar menyatu ke hatimu.
Dan di antara kita, hanya ada satu hati yang tepercaya.”
Waktu itu, memang tak ada siapa-siapa. Hanya kita
berdua. Sepasang kekasih yang dimabuk asmara.
Sepasang kekasih yang ingin milik-memiliki. Juga ingin
lebur-meleburi. Meski pada ujung-ujungnya, selalu
kau katakan: ”Aku pulang dulu, besok kita bertemu
lagi.” Dan aku, pun kembali kehilangan. Kehilangan
yang tak bisa dijelaskan dengan saksama.
(Gresik, 2016)
Gunung Wurung
Sore ini istriku makan. Dengan menu sayur bayam kalengan
yang ditambah lauk ikan tiruan. Lauk ikan tiruan yang kini
tinggal tulang-tulangnya: ”Tulang-tulang ikan tiruan.” Lalu,
istriku melihat kucing berbulu kawat. Kucing gemuk yang
mengeong-ngeong. Terus melemparkan tulang-tulang ikan
tiruan ke arah kucing. Kucing menerkamnya. Tapi tiba-tiba
tulang-tulang ikan tiruan berkelit. Dan berlompatan. Istriku
kaget. Sebab tulang-tulang ikan tiruan yang berlompatan
dikejar kucing. Seperti mengejar kupu-kupu transparan.
Kupu-kupu yang cerdik dan suka menggoda. Kata istriku:
”Lucu, lucu sekali mereka.” Aku mesem. Lalu hujan datang.
Istriku bergegas mengentasi jemuran di lantai atas dan
membawanya turun. Kali ini hujannya berwarna kuning.
Tidak biru seperti kemarin. Atau merah seperti kemarinnya
lagi. Hei, itu suara anak-anak tetangga yang berhujan-hujanan.
Tubuh dan pakaian mereka kuning. Juga kaca-kaca, tanda-tanda
jalan, dan trotoar yang terbentang pun kuning. Semuanya
kuning. Kuning yang terang. Di dapur (setelah melipati jemuran),
istriku memanaskan air: ”Kopi segera siap.” Aku mengangguk.
Tapi diam-diam menatap potret di dekat lemari pendingin.
Potret anakku yang sudah lama pergi dari rumah. Mencari
hidupnya sendiri. Hidup yang mengembara ke bumi yang lain.
Tapi tetap terasa begitu dekat. Bahkan saking dekatnya, aku
bisa merasakan rambatan dengus napas rindunya. Lalu, ketika
kopi terhidang (kopi hijau debu meteor), aku dan istriku duduk
di depan televisi. Saat itu, televisi memutar film ganjil. Tentang
tikus yang mampu mengubah wujudnya sesuka hati. Yang pada
akhir cerita, tikus pun merana. Sebab lupa pada wujud aslinya.
”Aku lupa pada wujud asliku, aku lupa pada wujud asliku!”
teriak tikus. Istriku terharu. Terus menghapus air matanya
yang merembes. Sedang, aku, segera masuk ke kamar mandi.
Di cermin, aku melihat wajahku yang melogam. Tapi mata
kananku kedap-kedip. Sebab, sudah saatnya baterai diganti.
Padahal, hari orbit masih menunjuk angka 33. Dan poliklinik
ulang-alik baru 666 jam lagi berkunjung. Diam-diam sebutir
pil bercahaya aku telan. Dan aku teringat pada legenda purba
yang kemarin aku unduh. Legenda tentang gunung yang
terbang. Lalu jatuh. Terus bangkit. Jadi gunung baru. Gunung
yang lebih gagah. Tapi gagal untuk terbang lagi. Gunung yang
jika ditelisik lebih dekat, selalu saja berdebar dan bergumam.
(Gresik, 2016)
Demi Obituari
: Harsono Sapuan
Di potret hitam-putih, pelukis duduk di batu. Di sebelah patahan batang kayu dan semak ilalang. Hanya sekuntum kembang yang tampak menyala di genggamannya. Sekuntum kembang yang terbasahi embun. Sekuntum kembang yang kata seseorang: ”Tanda ketika pelukis bersahabat dengan titik, lengkung, dan wewarna. Terus menuntunnya ke tempat-tempat yang ada di balik kabut.” Lalu, siapa yang akan ditemui pelukis?
Kata seseorang yang lain: ”Di sana, pelukis akan menemui apa yang kerap disebut sebagai ketidaktenteraman.” Yang membuat pelukis telentang di bawah gerimis yang merendah. Seperti telentangnya seekor ikan nekat yang megap-megap. Meski, siapa pun paham, kapan segalanya mesti bertahan, dan kapan pula mesti sebaliknya. Sebab, hukum sebab-akibat bagi daging dan darah, selalu leluasa mencari kemungkinannya sendiri.
Lalu, lewat tatapan mata pelukis dipotret, terlihatlah bintik kecil yang runcing. Yang saking runcingnya, akan terbayanglah hasrat yang tak bersyarat. Hasrat yang menjawili pikiran tak galib yang kerap menggeliat. Pikiran, yang ketika ada tujuh bintang rontok di relung subuh, pun menggumam: ”Kenapa para penghuni yang ada di ketinggian, gemar melemparkan sisa ledakan kembang apinya ke bawah?”
Jika kita membalik potret, akan terbacalah tulisan tipis: ”Di sini, mungkin tempat memulai. Mungkin juga tempat mengakhiri. Apa yang bergerak tak mungkin berbalik. Terus memanjang dan makin memanjang.”
(Gresik, 2016)
Mardi Luhung
Lahir di Gresik, Jawa Timur, 5 Maret 1965. Buku puisinya yang terbaru adalah Jarum, Musim dan Baskom (2015) dan Teras Mardi (2015). Ia tinggal dan bekerja sebagai guru di kota kelahirannya.
Sumber : Koran Kompas